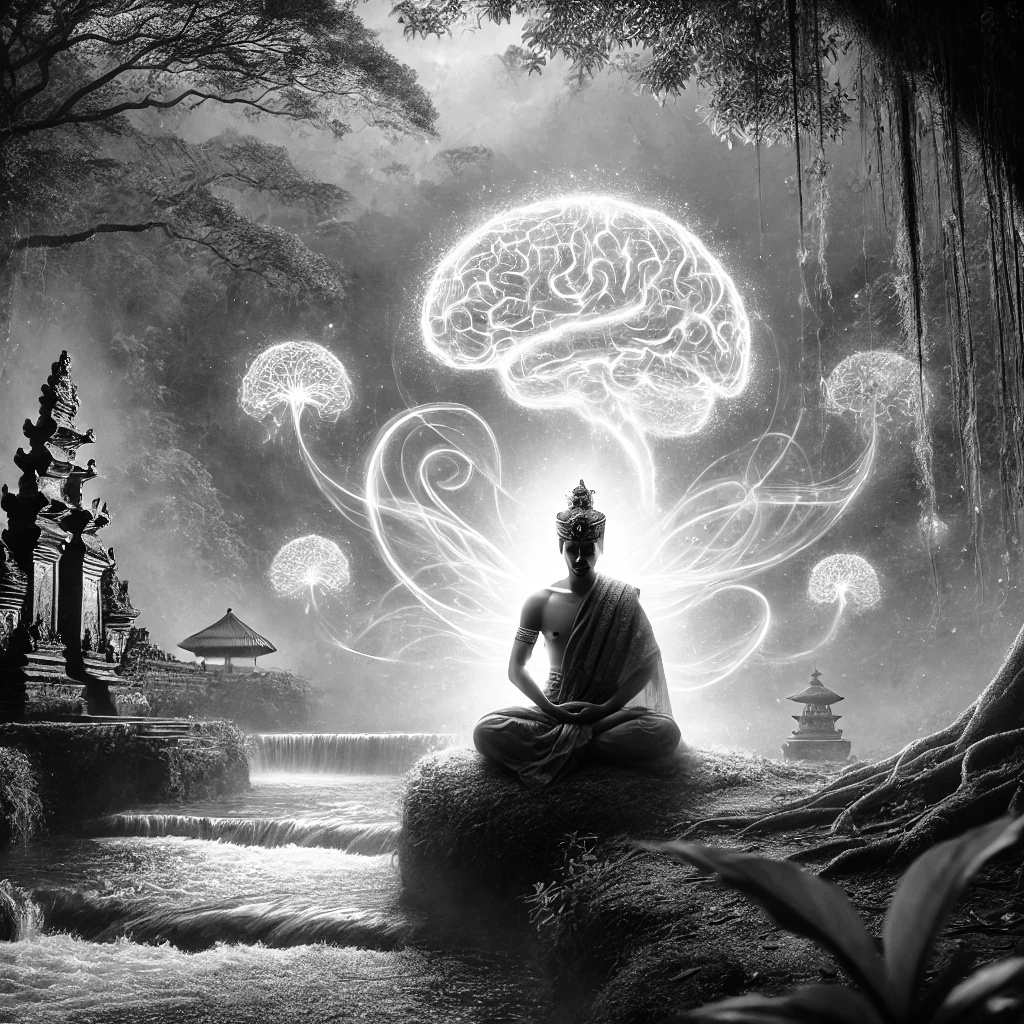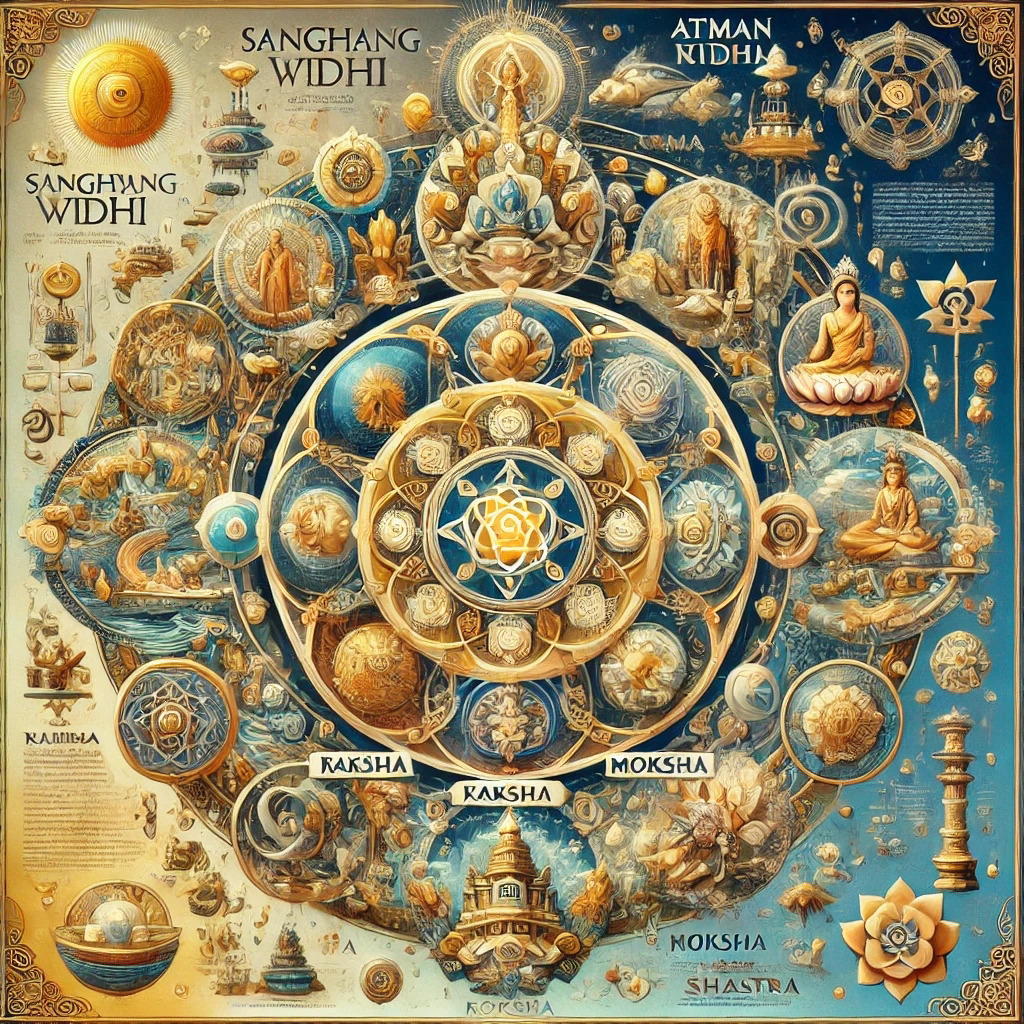Rekonstruksi Spiritualitas Nyepi: Pergeseran ke Tilem Kesanga Demi Keselarasan Kosmis
Oleh : IBN. Semara M.
Hari Raya Nyepi merupakan momentum spiritual yang menandai pergantian tahun dalam kalender Saka. Saat ini, Nyepi diperingati pada Penanggal Apisan Sasih Kedasa, dengan pelaksanaan Catur Brata Penyepian sebagai bentuk penyucian diri dan harmonisasi dengan alam semesta. Saya berpendapat, berdasarkan pertimbangan filosofis, kosmologis, serta kesinambungan energi spiritual dalam praktik Hindu Bali, bahwa pemindahan Nyepi ke Tilem Kesanga dengan pelaksanaan Pengerupukan pada Panglong 14 Sasih Kesanga merupakan langkah yang lebih sejalan dengan keseimbangan kosmis.
Pertimbangan ini muncul karena pelaksanaan Pengerupukan yang bertepatan dengan Tilem Kesanga berpotensi menimbulkan komplikasi energi, di mana energi Bhuta Yadnya dilepaskan bersamaan dengan momentum penyucian spiritual tertinggi. Oleh karena itu, memisahkan Pengerupukan dari Tilem dan menempatkan Nyepi pada Tilem Kesanga diyakini akan menjaga keseimbangan energi spiritual dengan lebih optimal.
Upacara Nyepi sebenarnya dimulai dari malam yang paling gelap disasih Kepitu, yang merupakan hari Siwa Latri, dilanjutkan dengan Tilem Kawelu sebagai hari Mesayut Tipat, dan berpuncak pada Nyepi di Tilem Kesanga, yang menandakan siklus terakhir dalam rangkaian spiritual ini.
Makna Angka 14 dalam Panglong 14 Sasih Kesanga dalam Filsafat Samkhya
Dalam filsafat Samkhya, angka 14 dalam Panglong 14 Sasih Kesanga memiliki makna simbolik yang merepresentasikan penyatuan Purusha (1)—kesadaran murni—dengan Prakriti (4)—unsur material pembentuk alam semesta. Penyatuan ini menghasilkan Panca (5), yang mencerminkan keseimbangan kosmis dalam berbagai aspek kepercayaan Hindu, seperti:
1. Panca Maha Bhuta: Lima unsur utama pembentuk alam (tanah, air, api, udara, ether).
2. Panca Sraddha: Lima keyakinan dasar dalam Hindu (Brahman, Atman, Karmaphala, Punarbhava, Moksha).
3. Panca Dewata: Lima manifestasi utama Brahman dalam agama Hindu.
4. Panca Yadnya: Lima jenis pengorbanan suci untuk menjaga keharmonisan alam dan spiritual.
5. Panca Kosa: Lima lapisan tubuh manusia dalam filsafat Hindu.
Dengan demikian, Panglong 14 Sasih Kesanga memiliki makna transendental sebagai fase peralihan antara kesadaran dan materi, yang berpuncak pada penyatuan kosmis dalam Tilem Kesanga. Hal ini menegaskan bahwa Tilem Kesanga lebih ideal sebagai Hari Raya Nyepi, karena menandai puncak refleksi spiritual dan pelepasan dari keterikatan material.
Tilem sebagai Hari Penyucian dan Saat Beryoganya Dewa Siwa dalam Pemberian Anugerah terhadap Ciptaan-Nya
Secara tradisional, Tilem diperuntukkan sebagai hari penyucian, baik bagi alam maupun bagi kesadaran manusia. Dalam ajaran Hindu. Tilem juga dianggap sebagai saat beryoganya Dewa Siwa dalam pemberian anugerah terhadap ciptaan-Nya, sebagaimana tersirat dalam kisah Lubdaka.
Kisah ini menggambarkan seorang pemburu yang tanpa sengaja melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa dengan berjaga sepanjang malam di atas pohon bilva, sambil menjatuhkan daun bilva ke sungai. Meskipun tanpa niat awal untuk beribadah, tindakannya menjadi bentuk bhakti yang tak disengaja, yang akhirnya membawanya kepada anugerah Moksa.
Oleh karena itu, tilem dianggap sebagai hari yang lebih sesuai untuk perayaan Nyepi, karena selaras dengan makna penyucian dan kontemplasi mendalam. Jika Pengerupukan dilakukan tepat pada tilem, maka energi Bhuta Yadnya yang dilepaskan dapat menimbulkan komplikasi energi yang berpotensi mengganggu kesinambungan spiritual umat Hindu. Dengan demikian, memindahkan Pengerupukan ke Panglong 14 dan memusatkan Nyepi pada Tilem Kesanga merupakan upaya menjaga keseimbangan energi spiritual.
Makna dan Peran Mesayut Tipat dalam Rangkaian Ritual Hindu
Dalam siklus ritual Hindu, Tilem Kawulu (Tilem Kewulu/Sasih Kawulu) merupakan hari yang diperuntukkan bagi Mesayut Tipat, sebuah ritus penyucian yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan spiritual masyarakat Hindu Bali.
Mesayut Tipat bukan sekadar praktik keagamaan, tetapi juga merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas berkah yang diterima. Ritual ini menjadi momen refleksi diri, di mana seseorang merenungkan tindakan yang telah dilakukan serta mencari pengampunan atas kesalahan yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidupnya.
Selain itu, Mesayut Tipat juga merupakan sarana untuk menghormati leluhur dan memohon bimbingan serta perlindungan mereka. Dengan mempersembahkan Tipat (ketupat) dalam ritual ini, umat Hindu mengungkapkan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis, seimbang, dan penuh berkah di masa mendatang.
Nyepi pada Pangelong 15 (Tilem) Sasih Kesanga dalam Perspektif Filsafat Samkhya
Pelaksanaan Nyepi pada Pangelong 15 (Tilem) Sasih Kesanga (9) memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan keseimbangan alam dan spiritualitas manusia.
Dalam filsafat Samkhya, angka 15 terdiri dari 1 dan 5, yang jika dijumlahkan menjadi 6, melambangkan Sad Ripu (enam musuh dalam diri manusia) dan Sad Tatayi (enam kebajikan yang menyeimbangkan sifat buruk). Tilem, yang merupakan fase gelap total dalam siklus bulan, mencerminkan keadaan tanpa ego, tanpa cahaya duniawi, sehingga menjadi waktu terbaik untuk moksha—pembebasan dari keterikatan material.
Sementara itu, angka 9 dalam Sasih Kesanga memiliki makna transendental dalam filsafat Samkhya. Angka ini melambangkan kesempurnaan spiritual dan kesadaran tertinggi, di mana manusia harus melampaui pengaruh Prakriti (alam material) dan menyatu dengan Purusha (kesadaran murni). Sasih Kesanga sendiri adalah puncak dominasi Bhuta Kala, di mana energi negatif mencapai intensitas tertinggi. Oleh karena itu, Nyepi pada Tilem Sasih Kesanga adalah momen terbaik untuk menetralkan energi tersebut, menyelaraskan diri dengan ritme kosmis, dan mencapai keharmonisan antara jiwa dan semesta.
Setelah Tilem, umat Hindu Bali memasuki Tahun Baru Saka, yang dimulai pada Penanggal 1 (Apisan) Sasih Kedasa (10). Angka 10 dalam filsafat Samkhya melambangkan kesempurnaan dharma, karena terdiri dari Dasadarma (sepuluh kebajikan utama dalam kehidupan). Peralihan dari Tilem Sasih Kesanga ke Penanggal 1 Sasih Kedasa mencerminkan transformasi dari kegelapan menuju cahaya, dari penyucian diri menuju awal kehidupan baru yang lebih harmonis. Oleh karena itu, Nyepi bukan hanya sekadar keheningan, tetapi juga sebuah siklus penyempurnaan spiritual yang membawa umat Hindu menuju kesadaran yang lebih tinggi dalam memulai tahun baru dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih.
Kesimpulan
Berdasarkan kajian filosofis, kosmologis, dan ritualistik, saya berpendapat bahwa pemindahan perayaan Nyepi ke Tilem Kesanga lebih selaras dengan prinsip spiritual Hindu. Pergeseran ini tidak hanya akan menciptakan sinkronisasi ritual yang lebih harmonis, tetapi juga menghindari konflik energi yang muncul akibat penyatuan Bhuta Yadnya dan penyucian spiritual dalam waktu yang berdekatan.
Selain itu, pemindahan ini juga akan lebih menyesuaikan diri dengan pola anugerah Dewa Siwa, sebagaimana diisyaratkan dalam kisah Lubdaka, di mana Tilem menjadi momen utama bagi pencapaian spiritual dan pencerahan. Dengan memisahkan Pengerupukan dari Tilem, diharapkan umat Hindu dapat lebih optimal dalam menjalankan Catur Brata Penyepian pada Hari Raya Nyepi, tanpa gangguan energi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut serta dialog bersama pemuka agama dan lembaga keagamaan guna mempertimbangkan implementasi perubahan ini dalam sistem penanggalan Hindu di Bali.
--------------